Oleh: Syaiful Arif
Telah enam tahun, sejak wafat pada 30 Desember 2009, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meninggalkan kita. Di Haul Ke-6 ini, perlu kiranya kita menengok kembali mimpi beliau akan republik ini terutama dalam konteks demokratisasi.
Telah enam tahun, sejak wafat pada 30 Desember 2009, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meninggalkan kita. Di Haul Ke-6 ini, perlu kiranya kita menengok kembali mimpi beliau akan republik ini terutama dalam konteks demokratisasi.
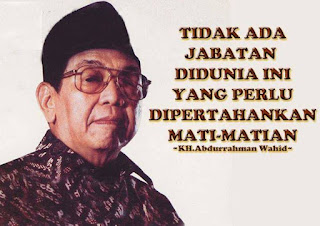 |
Sebagaimana diketahui, Gus Dur adalah pejuang demokrasi. Tidak hanya dalam pembelaan atas minoritas beragama dan ideologi, tetapi juga emansipasi atas ketertindasan mayoritas rakyat. MeminjamCarolCGould, kontur demokrasi Gus Dur berada di titik seimbang antara demokrasi politik dan demokrasi sosial. Inilah yang ia maksud dengan demokratisasi politik menuju struktur masyarakat berkeadilan.
Artinya, terwujudnya kebebasan dan partisipasi politik menjadi syarat bagi terpenuhinya hajat hidup rakyat. Maka tak heran jika Gus Dur menempatkan tiga nilai; syura (demokrasi), ‘adalah (keadilan), dan musawah (persamaan) sebagai pandangan-dunia (Weltanschauung) Islam. Ini berarti Islam adalah agama demokratik yang menyerukan keadilan sosial dan persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Semua pemikiran dan perjuangannya bersumber dari pandangan-dunia ini.
Dalam konteks ini terdapat tiga poin besar gagasan demokrasi Gus Dur. Pertama, demokrasi harus ditegakkan melalui kedaulatan hukum. Inilah yang membuatnya selaku ketua Pokja Forum Demokrasi (Fordem) menggagasperlunya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peradilan banding konstitusi. Ide ini sudah ia lontarkan pada 1992, jauh sebelum MK berdiri (Wahid, 1992:5).
Sebagaimana fungsi MK sekarang, Gus Dur saat itu menegaskan perlunya pendampingan atas rakyat dalam menghadapi undang-undang (UU) yang mencederai keadilan dan prinsip UUD 1945. Dalam kaca mata Jurgen Habermas, pandangan seperti ini menandai mimpi akan tegaknya negara hukum, di mana konstitusi menjadi “engsel” penyambung keterpisahan negara dan duniakehidupan (Lebenswelt).
Artinya, dengan mengajukan judicial review atas UU kontrarakyat melalui MK, masyarakat politik Indonesia sedang menuju penguatan negara hukum demokratik. Kedua, sebagai sistem politik, demokrasi merupakan “wasit ideologi” yang adil. Ia tidak hanya memberikan jalan bagi “Islam formalis” untuk berkontestasi dalam pemilu, namun juga memberikan rasa aman bagi kaum sekuler dan moderat karena semua ideologi harus disaring melalui pemilu.
Kemenangan sebuah ideologi tidak ditentukan melalui revolusi, melainkan kemampuannya memenangkan hati rakyat (Wahid, 1987:3). Ketiga, karena fokus pada pengembangan struktur politik berkeadilan, pandangan Islam demokratik Gus Dur terbebas dari sekularisasi dan integrasi (penyatuan agama dan negara). Dalam hal ini, pemikirannya lebih dekat dengan tradisi republikanisme daripada liberalisme.
Meskipun tak sepakat dengan pendirian negara Islam di Indonesia (dan sepakat jika didirikan di Timur-Tengah), solusinya bukanlah sekularisasi, melainkan perwujudan hakikat politik Islam melalui demokrasi. Pada titik ini, Gus Dur menekankan hakikat politik Islam yang bersumber dari tiga nilai Weltanschauung Islam di atas, dalam perjuangan Islam dan politiknya.
Maka itu, Gus Dur tak memerlukan negara Islam karena bahkan atas negara-bangsa (nation-state) sendiri, hakikat politik itu harus diperjuangkan. Artinya, yang terpenting dari politik Islam adalah mewujudkan hakikat politik, bukan formalisasi hukum Islam melalui negara. Ini selaras dengan pandangan republikan yang menempatkan kebaikan bersama (res publica) sebagai hakikat politik yang harus diwujudkan melalui demokrasi partisipatoris.
Dalam konteks ini kita melihat bahwa Gus Dur memang setuju dengan pemisahan agama dari negara, tetapi menolak perceraian Islam dari politik. Hanya, meskipun tak sepakat dengan negara Islam, Gus Dur tetap mengamini penegakan syariah dalam naungan NKRI.
Penegakan itu dilakukan melalui; (1) penerapan partikel hukum Islam (waris, nikah, wakaf, dan haji) dalam kerangka hukum nasional; (2) menjadikan syariah sebagai etika sosial di masyarakat (Wahid, 1982:6). Maka itu, perjuangan Islam demokratiknya merupakan penegakan etika sosial Islam yang mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar manusia.
Relevansi Pemikiran
Lalu, apa relevansi gagasan Gus Dur ini? Tentu ia bermimpi bahwa politik kita tak lagi terjebak dalam “demokrasi seolaholah” sebagaimana dialaminya di masa Orde Baru. Sebuah praktik manipulatif, di mana demokrasi hanya ditandai oleh keberadaan lembaga-lembaga negara, namun raib sebagai kualitas kehidupan politik. Faktanya, Gus Dur sudah mewujudkan mimpinya itu, melalui pemenuhan hak sipil dan politik rakyat ketika menjabat presiden ke-4 RI.
Penegakan supremasi sipil, pengembalian TNI ke barak, penghapusan Bakorstanas, Litsus, serta Departemen Penerangan adalah upayanya agar masyarakat sipil menikmati kebebasan berserikat dan berpendapat dalam demokrasi tak seolaholah. Hanya, mimpinya akan struktur masyarakat berkeadilan belum juga menjadi ujung dari praktik demokrasi. Hal ini terjadi Karena kita mengalami pergeseran kesemuan demokrasi, dari “kesemuan institusional”, menuju “kesemuan prosedural”.
Artinya, ketika kita telah menikmati institusi dan prosedur politik demokratis, kita masuk dalam jebakan “kesemuan prosedural” karena tujuan demokrasi dibajak oleh para pengguna prosedur tersebut. Dalam konteks ini, kita perlu menjadikan definisi demokrasi Gus Dur sebagai batasan utama demokrasi.
Artinya, sejauh struktur masyarakat berkeadilan belum terbentuk, sejauh itu pula demokrasi belum ditegakkan, meskipun segenap prosedurnya telah dilaksanakan. Pada titik inilah umat Islam perlu bersatu untuk mewujudkan tujuan utama demokrasi. Hanya, menurut Gus Dur, selama kaum muslim belum beranjak dari “relativisme kelompok” menuju perjuangan kemanusiaan universal, selama itu pula agama lebih menjadi hambatan daripada pendorong demokratisasi.
Diperlukan kesadaran untuk mendudukkan Islam “satu meja” dengan demokrasi demi pemuliaan harkat manusia yang telah ditegaskan Alquran yang suci (17:70). []
Sumber:
KORAN SINDO, 30 Desember 2015
Syaiful Arif | Dosen Mata Kuliah Pemikiran Gus Dur, Pascasarjana STAINU Jakarta
Sumber:
KORAN SINDO, 30 Desember 2015
Syaiful Arif | Dosen Mata Kuliah Pemikiran Gus Dur, Pascasarjana STAINU Jakarta